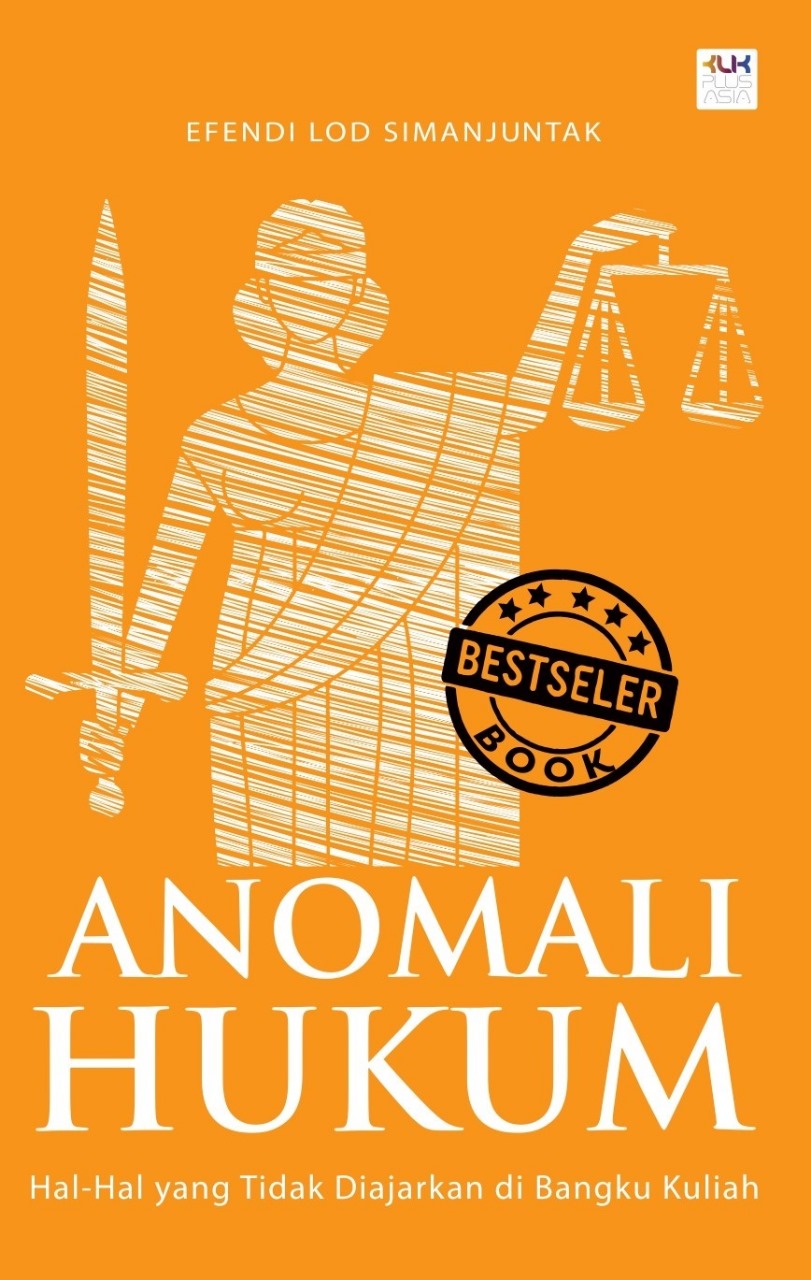Keterangan Buku :
Judul Buku: Anomali Hukum: Hal-Hal yang Tidak Diajarkan di Bangku Kuliah
Penulis: Efendi Lod Simanjuntak
Penerbit: Klikplus Asia
Cetakan: II, 2025
Tebal: 129 halaman
ISBN: 978-623-88073-8-3
Di ruang kelas fakultas hukum, mahasiswa sering kali dilatih menjadi penjaga teks. Mereka diajarkan membaca pasal, menafsirkan ayat, merumuskan dakwaan, menyiapkan pembelaan. Buku-buku tebal berjejer di rak perpustakaan — mulai dari asas hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, hingga teori keadilan. Semua disusun rapi, seolah dunia hukum berjalan dalam jalur lurus, tertib, dan dapat diprediksi.
Namun, Efendi Lod Simanjuntak, lewat bukunya Anomali Hukum: Hal-Hal yang Tidak Diajarkan di Bangku Kuliah, ingin menunjukkan pada pembaca bahwa di balik rapinya teks, praktik hukum justru penuh tikungan, tabrakan kepentingan, dan jebakan moral yang tidak selalu sederhana. Celah-celah itu sering tak tertulis di modul kuliah, tapi jadi “kebiasaan umum” di arena penegakan hukum.
Buku ini memotret realitas hukum Indonesia dengan nada setengah membongkar, setengah mengingatkan. Isinya adalah kompilasi tema-tema pendek, lugas, praktis — 60 pokok bahasan, mulai dari seluk-beluk putusan pidana, mitos presumption of innocence, dilema advokat, hubungan kuasa antara klien dan pengacara, sampai paradoks keadilan. Semua dibentangkan dengan gaya cerita praktisi: ringkas, tapi meninggalkan pertanyaan panjang di benak pembaca.
Sejak halaman awal, Efendi menegaskan bahwa hukum di Indonesia kerap berwajah ganda. Di satu sisi, hukum tampil meyakinkan di teks: pasal berlapis, sanksi tegas, prosedur detail. Tapi, di lapangan, hukum bisa ditekuk, ditunda, diperdagangkan. Di satu kasus, orang kecil diadili cepat, putusannya berat. Di kasus lain, orang besar bisa bersembunyi di balik celah pembuktian yang lambat, saksi yang bungkam, atau birokrasi yang sengaja diperlambat.
Bagian-bagian seperti “The Myth Behind ‘Presumption of Innocence’” dan “The Paradox of Justice” mengajak pembaca menengok praktik sidang pidana yang sering kali tidak seterang lampu ruang sidang. Prinsip praduga tak bersalah memang diagungkan di buku teks — tapi dalam praktiknya, sering diabaikan oleh opini publik, tekanan media, bahkan penegak hukum sendiri.
Pada bab-bab lain, penulis membongkar situasi yang jarang diulas di kelas: dilema advokat yang harus menyeimbangkan loyalitas pada klien dengan kewajiban moral pada kebenaran. Haruskah seorang pengacara selalu bicara jujur, padahal tugasnya membela sekuat mungkin? Apa yang harus dilakukan ketika klien bersikap setengah terbuka? Bagaimana posisi advokat saat berhadapan dengan aparat penegak hukum yang lebih berkuasa?
Isi dari buku ini memanjang ke ranah lebih teknis: bagaimana menghadapi saksi bermasalah, cara mendiskreditkan saksi, strategi memaksa saksi bicara, hingga cara membaca arah sidang yang sering kali tidak tertebak. Tema-tema semacam “Evidence vs Emotion”, “Hard Evidence vs Clues”, atau “How to Deal with Witness” menjadi ruang belajar praktis, terutama bagi advokat muda yang baru menjejak arena peradilan.
Bagian yang menohok justru ketika penulis menyoroti jebakan moral profesi hukum. Lewat tema “The Enemy is My Client”, penulis menyinggung bahwa advokat tidak selalu berdiri membela kebenaran objektif. Kadang ia terpaksa membela kepentingan klien dengan moral yang dapat dikatakan “abu-abu” — karena begitulah prinsip right to counsel bekerja. Inilah wilayah abu-abu yang sering hanya disentuh di kuliah etika, tetapi jarang benar-benar dihadapi sebelum praktik.
Penulis juga menyinggung ruang yang lebih gelap: negosiasi di balik meja, kompromi, lobi-lobi perkara, stigma advokat yang “bermain dua kaki”, atau aparat yang dengan mudah memanfaatkan celah ketidaktahuan klien. Tema-tema ini sengaja ditulis pendek, namun menohok — seolah ingin menunjukkan bahwa semakin seseorang tahu celah, semakin besar peluang ia jatuh pada godaan menyalagunakan kuasa.
Meski penuh kritik, buku ini tidak jatuh menjadi kumpulan sinisme. Efendi tetap menekankan: memahami anomali bukan untuk membenarkan penyimpangan, melainkan agar praktisi hukum punya kewaspadaan dan keberanian untuk mengoreksi dari dalam. Pasalnya, bagaimanapun, hukum hanya bisa berdiri tegak kalau orang-orang di dalamnya berani meluruskan jalan yang bengkok.
Bagian menarik lainnya adalah bagaimana penulis merangkum tip praktis untuk publik, bukan hanya untuk pengacara. Topik seperti bagaimana menghadapi gugatan pencemaran nama baik, bagaimana menyiapkan diri menghadapi perkara pidana, sampai mekanisme penanganan buronan lintas yurisdiksi, memperlihatkan bahwa buku ini juga bisa dibaca oleh masyarakat umum — agar tidak mudah gamang ketika berhadapan dengan situasi dilematis.
Tidak ada teori rumit di sini. Hal yang ada adalah potongan-potongan pengalaman di ruang sidang, kantor hukum, meja mediasi, dan rapat gelap di balik berita. Disusun dengan bahasa populer, buku ini cocok menjadi teman duduk mahasiswa hukum semester akhir yang sebentar lagi akan menghadapi skripsi dan PKL. Buku ini juga relevan bagi praktisi muda yang sering dibenturkan antara idealisme buku teks dan praktik lapangan.
Membaca Anomali Hukum membuat kita sadar, bahwa di balik sistem hukum yang tebal dengan pasal dan ayat, pada akhirnya ia dijalankan oleh manusia. Sementara, manusia, kata sang penulis, selalu membawa celah. Untukk itulah, membangun keadilan tidak cukup dengan menambah pasal atau menebalkan KUHP. Hal yang dibutuhkan adalah integritas, nyali, dan konsistensi moral di titik-titik paling rapuh.
Dari sampul oranye yang kontras, dengan ilustrasi Dewi Keadilan yang hanya digambar garis — pesan simboliknya jelas: hukum di Indonesia memang punya bentuk, tapi garisnya sering kabur, putus sambung, kadang tidak utuh. Kita, pembaca dan praktisi, ditantang merangkainya lagi agar tetap tegak.
Anomali Hukum tidak akan menjawab tuntas pertanyaan “bagaimana membenahi hukum Indonesia?”. Ia cukup jujur membisikkan: hukum itu rapuh, praktiknya tak pernah steril, dan jika kita menutup mata, celah-celahnya akan terus melebar. Di situlah buku ini mengandung keberanian kecil: membuka ruang diskusi, memancing debat, dan menampar kesadaran kita agar tidak tenggelam dalam ilusi bahwa hukum selalu suci.
Mungkin inilah sumbangan paling jujur buku ini: memotret wajah hukum kita apa adanya — dengan paradoks, retak, dan lubangnya — sambil mengingatkan, bahwa di ujung jalur panjang bernama penegakan hukum, ada nurani yang tidak bisa disubkontrakkan pada pasal.